beritaalternatif.com – Rabu (18/5/2022) lalu, dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando kembali muncul dalam video yang ditayangkan Cokro TV setelah ia dirawat karena kasus pengeroyokan dan pemukulan dalam aksi mahasiswa di kawasan Gedung DPR RI pada 11 April 2022.
“Sebagian orang bertanya, apakah saya akan tetap kritis terhadap Islam? Saya tidak kritis terhadap Islam. Yang saya kritik adalah penafsiran terhadap Islam. Itu adalah dua hal yang berbeda,” ucap Ade sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Cokro TV, Jumat (20/5/2022) siang.
Ia mengaku percaya bahwa Islam adalah agama yang membawa ajaran perdamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Namun, karena penafsirannya yang dinilai Ade salah, Islam seolah menjadi sumber perpecahan, kebencian, dan kekerasan.
“Saya harus sampaikan itu. Justru karena sebagai seorang Muslim, saya harus menegakkan kebenaran. Kadang itu akan membawa risiko yang besar, bahkan sangat besar. Tapi jalan itu harus saya tempuh karena saya merasa memiliki pemahaman, memiliki kepintaran untuk menyampaikannya, dan mungkin juga memiliki pengaruh,” jelasnya.
Karena itu, lanjut dia, mengkritik cara penafsiran Islam yang sempit adalah kewajiban baginya, apa pun risiko yang harus dihadapi Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) tersebut.
Ade pun mengisahkan perjuangan Farag Fouda, seorang pemikir, penulis, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), dan kolumnis berpengaruh di Mesir. Fouda sejatinya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam studi Islam. Ia justru menyandang gelar doktor di bidang ekonomi pertanian.
Namun, Fouda secara tekun mempelajari Islam melalui buku-buku yang terentang dari kepustakaan klasik hingga karya-karya mutakhir para pembaharu Islam.
Dari kekayaan pengetahuannya, Fouda pun tiba pada keyakinan tentang arti penting penafsiran ulang Islam agar Islam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mutakhir di Mesir. “Karena sikapnya itu, Fouda berhadapan dengan kaum Islam radikal di Mesir,” bebernya.
Kaum radikal tersebut percaya bahwa umat Islam harus menjalankan ajaran-ajaran Islam seperti yang dulu diterapkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di abad ke-7 Masehi.
Ia menyebutkan, kaum radikal mempercayai bahwa Mesir mengalami kemunduran karena meninggalkan agama. Mereka juga percaya bahwa Mesir harus menjadi negara yang menegakkan syariat Islam.
Sebaliknya, Fouda berpendapat, umat Islam tidak bisa begitu saja mengikuti apa pun yang dikatakan para ulama sebelumnya. Sebab, agama adalah ajaran yang harus selalu dihidupkan kembali sesuai perkembangan zaman.
Fouda meyakini bahwa tunduk dan patuh pada doktrin-doktrin lama justru akan membawa kehancuran pada Islam. Karena pandangannya itu, Fouda dianggap sebagai pemikir liberal.
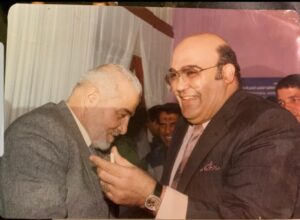
Dalam hidupnya, ia selalu menyuarakan kebebasan berpikir dan berekspresi. Dia juga sangat percaya arti penting ijtihad, yakni penggunaan akal sehat secara serius dalam menjawab persoalan-persoalan Islam di tengah masyarakat.
Fouda menolak penerapan syariat Islam secara formal. Ia juga menentang sistem khilafah. “Dia mengecam tumbuhnya kekuatan Islam radikal yang dibiarkan oleh pemerintah sekuler Mesir, meski jelas-jelas kelompok radikal Islam telah membunuh Presiden Anwar Sadat,” terang Ade.
Tokoh Mesir itu juga mengecam pemerintah atas tumbuhnya penafsiran Islam yang sempit di negeri yang dijuluki Ardh Al-Anbiya tersebut. Fouda juga menentang argumen kaum radikal yang mengharamkan bank karena dianggap melegalkan riba.
“Dia memperjuangkan kesamaan hak bagi seluruh warga Mesir tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lainnya. Ia tegas memperjuangkan kemerdekaan beragama,” terangnya.
Semula Fouda bergabung dengan Partai Al-Wafd. Namun pada 1984, ia keluar karena partai tersebut berkoalisi dengan partai Islam radikal, Ikhwanul Muslimin, dalam pemilihan parlemen.
Intelektual Mesir tersebut meyakini tentang ide pemisahan agama dan negara. Dalam tulisan-tulisannya, ia mengkritik kelemahan cara pandang kaum Islam radikal, yang menurutnya tidak mau mendialogkan agama dan modernitas.
Fouda juga dengan berani mengungkapkan sejarah kelam Islam. Ia menulis artikel berdasarkan sumber sejarah Islam yang otoritatif.
“Dia tidak mengarang bebas. Dia menggunakan buku-buku yang sebenarnya juga dibaca oleh kaum Islam radikal yang membencinya,” ungkap Ade.
Kelompok radikal Mesir sangat senang menggelorakan kegemilangan Islam di zaman Nabi dan masa kekuasaan sahabat Nabi.
Diketahui, setelah Nabi wafat, umat Islam dipimpin oleh sahabat Nabi: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Tholib. Setelah itu, umat Islam memasuki era kepemimpinan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah.
Kelompok Islam radikal Mesir percaya bahwa era tersebut merupakan masa kejayaan yang harus dijadikan teladan bila Islam ingin kembali mencapai kejayaannya.
“Ini yang dibantah oleh Fouda. Dia bahkan menyatakan bahwa sejarah Islam di masa lalu itu, selain menunjukkan kegemilangan, juga memiliki banyak jejak memalukan. Tiga dari empat sahabat Nabi terdekat yang menjadi pemimpin Islam pasca Nabi Muhammad justru wafat karena pembunuhan politik oleh kelompok-kelompok Islam sendiri yang saling berseteru,” ungkapnya.
Fouda juga mengungkap sejarah bahwa di zaman Dinasti Umayyah dan Abbasiyah “banyak khalifah yang brutal dan biadab”. Ia menguraikan kebiasaan sejumlah khalifah yang hedonis, korup, dan main perempuan.
Penulis Mesir itu menyebutkan, pendiri Dinasti Abbasiyah adalah seorang penjagal karena mengundang 90 anggota keluarga Dinasti Umayyah makan malam dan menyiksa mereka sebelum kemudian membunuhnya.
Keberanian Fouda melontarkan kritik dan mengungkap fakta tentang sisi kelam dunia politik Islam harus dibayar mahal. Ia dicap melecehkan dan menodai Islam.
Organisasi Islam radikal Mesir, Jamaah Islamiyah, menyebutkan bahwa Fouda murtad karena menolak penerapan syariat Islam. Sekelompok ulama di Mesir juga menyatakan Fouda telah menghujat Islam, bahkan dia dianggap telah keluar dari Islam karena pemikiran dan tulisan-tulisannya.
Pada 8 Juni 1992, dia tewas ditembak mati dua orang simpatisan Jamaah Islamiyah. Sebelum dibunuh, Fouda memang dengan berani muncul dalam perdebatan publik menghadapi tiga orang tokoh Islam radikal. Dua tokoh sekuler lainnya memilih tidak hadir dalam debat itu.
Banyak teman Fouda mengingatnya agar ia tidak memenuhi permintaan debat tersebut. Fouda menjawab bahwa dia harus menyampaikan kebenaran yang diyakininya walaupun untuk itu ia harus mati.
Sejumlah pihak menilai bahwa dalam debat itu Fouda unggul dalam segala hal. Ia dengan jernih mematahkan argumen-argumen yang dilontarkan tiga pembicara lainnya.
Namun, karena itulah ia menjadi tokoh yang terlalu menakutkan bagi kelompok radikal. Fouda dibunuh bukan karena menyesatkan umat, tetapi karena ia berani menyampaikan kebenaran kepada umat Islam.
Ulama terkenal Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, tampil sebagai saksi ahli di pengadilan untuk membela dua orang pembunuh Fouda. Al-Ghazali menyatakan bahwa pemerintah bertugas untuk menghukum mati mereka yang dinilai murtad dari Islam.
Menurut Al-Ghazali, bila pemerintah tidak mampu melakukannya, maka orang lain memiliki hak untuk menghukum mati Fouda.

Ironisnya, pembunuh Fouda tak memahami karya-karya tokoh Mesir tersebut. Salah satu di antaranya mengaku tidak paham karya Fouda karena ia tak bisa membaca. Ia membunuh kolumnis kenamaan itu karena seruan pemimpinnya.
“Saya bercerita ini bukan untuk membandingkan Fouda dengan saya. Pengetahuan dan keberanian saya jauh di bawah Fouda. Tantangan Mesir juga jauh lebih berat daripada Indonesia,” kata Ade.
“Tapi yang ingin saya katakan, memperjuangkan kebebasan dan keterbukaan dalam beragama itu adalah sebuah kewajiban yang penuh mengandung risiko. Tapi tidak boleh ada langkah mundur,” lanjutnya.
Kasus Fouda adalah contoh yang baik bagi Indonesia. Setelah ia tewas, kelompok-kelompok radikal tumbuh menguat. Akibatnya, ketika terjadi revolusi Mesir yang menggulingkan Presiden Mubarak, dengan segera kaum radikal mengambil alih kekuasaan melalui pemilu.
Islamisasi pun diterapkan di Mesir, yang kemudian melahirkan diskriminasi agama, konflik politik, dan kehancuran ekonomi.
Serangan balik segera terjadi. Pihak militer mengudeta kaum Islam radikal. Bahkan puluhan anggota Ikhawanul Muslimin dihukum mati.
“Karena itu, kita tidak boleh berhenti menegakkan kebenaran. Kalau kita biarkan benih-benih radikalisme itu tumbuh tanpa ditentang, Indonesia bisa menjelma menjadi Mesir atau negara-negara Timur Tengah lainnya,” terang Ade.
“Memang pasti ada risiko. Tapi kita harus percaya, Allah akan selalu berada bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin





















