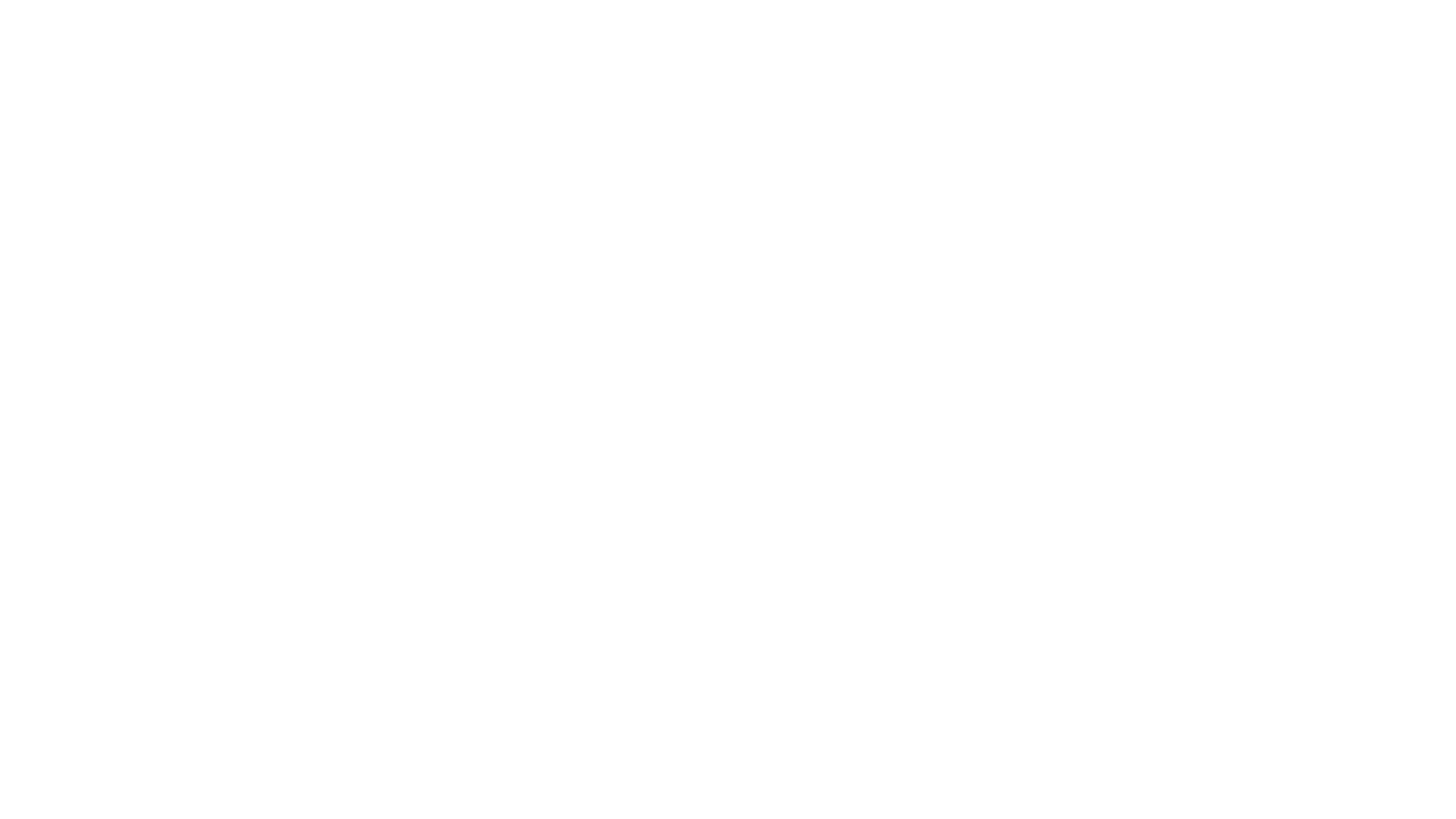Oleh: Dr. Aji Sofyan Effendi*
Kita patut menghargai dan mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara kepada kampus-kampus di Indonesia. Kebijakan ini berangkat dari keinginan pemerintah untuk membantu penguatan kapasitas fiskal, yang selama ini potensi untuk pembiayaan kampus semakin besar sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman.
Untuk menjadi kampus yang go internasional, butuh biaya besar dan upaya untuk menyejahterakan kampus baik dari sisi penerimaan dosen, tendik, maupun operasional kampus yang semakin membengkak, dalam rangka pemenuhan tri dharma perguruan tinggi.
Di sisi lain, APBN memiliki keterbatasan, namun senyampang dengan kebijakan itu, pemberian IUP Pertambangan Batu Bara ternyata telah menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini menghadapi tantangan besar terkait pengalaman institusi pendidikan dalam mengelola industri pertambangan serta potensi risiko hukum yang dapat timbul.
Pemberian IUP batu bara kepada perguruan tinggi menimbulkan beberapa risiko, di antaranya:
Pertama, kurangnya pengalaman dalam sektor pertambangan. Kampus sebagai institusi pendidikan lebih berfokus pada pengembangan keilmuan, riset, dan inovasi. Mengelola industri pertambangan memerlukan keahlian teknis, manajerial, dan regulasi yang tidak dimiliki oleh sebagian besar perguruan tinggi.
Kedua, potensi konflik hukum dan etika. Pemberian IUP kepada kampus berpotensi menimbulkan resistensi hukum, baik dari segi kepatuhan terhadap regulasi pertambangan maupun konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ketiga, dampak lingkungan dan sosial. Pertambangan batu bara memiliki dampak ekologis yang signifikan. Jika dikelola tanpa pengalaman dan standar keberlanjutan yang memadai, kampus berisiko menghadapi kritik dari masyarakat dan aktivis lingkungan.
Pola Dana Bagi Hasil
Dari permasalahan tersebut di atas, penulis menawarkan konsep lain, yaitu berupa:
Sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dan minim risiko, pola pendanaan melalui DBH dari pendapatan negara, sektor pertambangan batu bara dapat menjadi solusi yang lebih tepat. Pola ini memungkinkan kampus-kampus yang berada di daerah kaya sumber daya batu bara untuk menerima alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan kontribusi daerahnya terhadap penerimaan negara.
Beberapa keuntungan dari skema DBH ini antara lain:
Pertama, minim risiko hukum dan operasional. Kampus tidak perlu terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, sehingga menghindari potensi sengketa hukum serta konflik kepentingan dalam pengelolaan SDA.
Kedua, fokus pada pengembangan akademik dan riset. DBH dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan, beasiswa, penelitian, serta program pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam.
Ketiga, mendorong pemerataan dan kesejahteraan kampus berbasis SDA. Skema DBH dapat didistribusikan kepada kampus-kampus yang berada di daerah penghasil batu bara, seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Riau, dan Aceh, sehingga meningkatkan kapasitas dan daya saing akademik secara merata.
Dalam konteks peningkatan kesejahteraan kampus, pemberian IUP batu bara bukanlah solusi ideal mengingat kompleksitas dan risiko yang menyertainya. Alternatif yang lebih rasional dan berkelanjutan adalah melalui skema DBH dari sektor pertambangan batu bara.
Dengan pola ini, kampus tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari SDA tanpa harus terlibat langsung dalam industri pertambangan yang berisiko tinggi. Implementasi kebijakan ini perlu didukung dengan regulasi yang jelas agar alokasi dana benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Data dan Fakta
Data yang dimiliki penulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM hingga kuartal III 2023 sebesar Rp 224 triliun. Angka ini setidaknya telah mencapai 99,90% dari target yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp 225 triliun.
Moncernya realisasi PNBP sektor ESDM didongkrak oleh pendapatan SDA sub-sektor mineral dan batu bara (minerba) yang melesat melebihi dari target tahun 2023 hingga 155,93%.
Dari target yang dicanangkan, PNBP minerba sudah mencapai Rp 132 triliun dari target Rp 85 triliun, atau secara persentase mencapai 155,93%.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, PNBP dari sub sektor minerba utamanya berasal dari peningkatan iuran produksi atau royalti batu bara, dan merupakan dampak dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM.
Meski rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) mengalami penurunan selama periode bulan Januari sampai dengan Agustus 2023, namun kenaikan tarif royalti batu bara mampu menutupi penurunan HBA tersebut.
Sepuluh Daerah Penghasil Utama Batu Bara
Pertama, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur mencatat cadangan batu bara terbesar di Indonesia dengan 11,59 miliar ton, menyumbang sekitar 38% dari total cadangan nasional. Daerah ini menjadi pusat pertambangan batu bara dengan pengembangan industri yang pesat.
Kedua, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menempati posisi kedua dengan cadangan batu bara sebesar 8,67 miliar ton. Pada November 2023, daerah ini mencatat produksi sebesar 90 juta ton, yang merupakan angka produksi tertinggi dalam sejarah pertambangan di Sumatera Selatan.
Ketiga, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan memiliki cadangan batu bara sebesar 3,91 miliar ton. Dengan cadangan yang signifikan, daerah ini memainkan peran penting dalam pasokan batu bara nasional.
Keempat, Kalimantan Tengah. Ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya, menjadi pusat pertambangan batu bara dengan cadangan sebesar 2 miliar ton, menjadikannya penghasil batu bara terbesar keempat di Indonesia.
Kelima, Jambi. Jambi, yang terletak di tengah Pulau Sumatera, memiliki cadangan batu bara sebesar 1,66 miliar ton. Daerah ini terus berkembang sebagai salah satu pusat produksi batu bara di Indonesia.
Keenam, Kalimantan Utara. Dengan cadangan batu bara sebesar 531,57 juta ton, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan cadangan terendah di antara provinsi-provinsi Kalimantan lainnya, namun tetap merupakan penghasil batu bara signifikan di Indonesia.
Ketujuh, Aceh. Terletak di ujung Pulau Sumatera, Aceh memiliki cadangan batu bara sebesar 428,65 juta ton, menjadikannya penghasil batu bara terbesar ketujuh di Indonesia.
Kedelapan, Riau. Riau menyimpan cadangan batu bara sebesar 359,12 juta ton. Sebagai salah satu provinsi di Pulau Sumatera, Riau berkontribusi signifikan terhadap produksi batu bara nasional.
Kesembilan, Bengkulu. Bengkulu, yang juga terletak di Sumatera Selatan, memiliki cadangan batu bara sebesar 103,3 juta ton. Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain, Bengkulu tetap menjadi produsen batu bara penting.
Kesepuluh, Sumatera Barat. Sumatera Barat menempati posisi terakhir dengan cadangan batu bara sebesar 23,63 juta ton. Meskipun cadangannya relatif kecil, daerah ini tetap berperan dalam industri batu bara nasional.
Exercise DBH Batubara
Dari data penerimaan batu bara dalam APBN tersebut di atas, untuk menentukan DBH batu bara bagi kampus di Kaltim, dapat dilakukan exercise sebagai berikut:
Jumlah Universitas di Kaltim:
- 1 PTN, 9 PTS
- Sekolah tinggi: 28 Sekolah Tinggi
- Poltek: 6 Poltek
Total: 44 Kampus
Sebagai kontributor utama penyumbang APBN dari sektor batu bara Kaltim adalah urutan 1 dari 10 daerah penghasil batu bara di Indonesia, yaitu sebesar 38%, ini berarti:
- Penerimaan negara dari batu bara= Rp 132 triliun
- 38% dari Kaltim= Rp 50,26 triliun
- Diasumsikan DBH BB untuk Kampus= 25%
Maka DBH kampus Kaltim dari batu bara= 12,56 triliun
Alokasi masing-masing kampus:
Syarat utama, akreditasi unggul 60%, sangat baik 30%, dan baik 10%.
Alokasi masing-masing kampus di Kaltim:
- Akreditasi unggul= 3 kampus
- Akreditasi sangat baik= 20 kampus
- Akreditasi baik= 21 kampus
Dengan demikian, maka besaran nominal kampus di Kaltim berdasarkan kriteria akreditasi adalah sebagai berikut:
- 3 kampus masing-masing menerima 2,51 triliun
- 20 kampus masing-masing menerima 18,84 miliar
- 21 kampus masing-masing menerima 5 miliar
Dengan exercise tersebut terlihat bahwa kampus akan memiliki kemampuan kapasitas fiskal yang jauh lebih bagus sehingga dapat dipastikan, selain memperoleh kemakmuran, juga akan mampu mendongkrak tri dharma perguruan tinggi yang saat ini sedang kekurangan oksigen, tanpa menimbulkan resistensi hukum dan etika.
Hal yang sama excercise tersebut di atas dapat diterapkan di 10 daerah penghasil batu bara sesuai dengan kontribusinya masing-masing dalam APBN. Itu pun bagi Kaltim hanya 25% dari kontribusi Kaltim sebesar 38% atau dari Rp 50,26 triliun hanya Rp 12,56 triliun. (*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda)